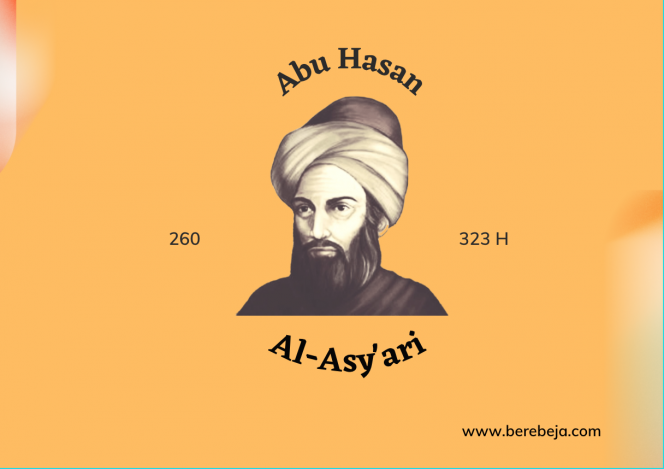BANDUNG, berebeja.com – Pemahaman agama yang kita anut menuntut adanya presentasi yang lebih besar tentang masalah Ilmu kalam atau teologi Islam. Karena, dalam pandangan Islam mengetahui tentang teologis begitu penting, atau suatu yang sangat mendasar bagi kehidupan beragama, tentang kesadaran yang peka terhadap eksistensi Tuhan.
Sehingga llmu kalam bisa disebut sebagai teori ke-tuhanan adalah ilmu yang sangat melandasi masalah yang berkaitan dengan Maha Kuasa. Kesadaran atas keagungan-Nya dalam keyakinan agama Islam begitu penting untuk diimani, demikian pula dalam keyakinan imani alam semesta pun merupakan argumentasi (dalil) wudjud atas realitas Tuhan.
Namun demikian tak semua sumber mengatakan atau tidak tidak sepenunya bersandar pada argumentasi tersebut. Tak terkecuali tuntunan moral etik, yang secara psikologis bahkan merupakan penekanan iman dan tindakkan sebagai teori ke-Tuhanan dalam klasifikasinya. Jika kita baca literatur-literatur klasik Islam, para sarjana Islam dahulu banyak sekali mencurahkan pemikirannya tentang teori ke-Tuhanan tersebut, dalam khasanah kesarjanaan muslim klasik biasa di sebut Ilm al-Kalam.
Menurut sejarawan Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1406 M) bagi dia Ilmu Kalam merupakan pengetahuan yang menghimpun dalil-dalil tetang topik-topik iman yang berlandaskan argumentasi-argumntasi logika (al-‘Aqliyah).
Dalam pembahasanya, ilmu kalam memiliki peran sangat penting. Posisi ilmu tersebut setidaknya ada enam topik yang paling umum di bahas dalam ilmu kalam itu; Pertama, topik ketuhanan (al-Uluhiyah), Kedua, tentang kenabian (al-Nubuwah), Ketiga, topik mengenai Kepemimpinan (al-Imamah), Keempat tetang hari pembalasan (al-Ma’ad).
Sebagai epistemologi, ilmu kalam (teologi Islam) kerap banyak memperbincangkan tentang wujud Allah (being), sifat-sifat-Nya, dan persoalan para nabi dan rasul, serta berita-berita yang berhubunagn dengan hari akhir, bahkan tetang kepemimipinan dalam agama.
Dari sekian banyak tokoh muslim di abad lampau, salah satunya tokoh yang sangat menonjol dalam kesarjanaan Islam klasik, ialah seorang teolog klasik bernama Abu Hasan al-Asy’ari, ia merupakan tokoh sangat penting dalam perkembangan ilmu kalam dan tonggak penting ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah.
Memperbincangkan seorang tokoh seperti Al-‘Asy’ari sangatlah menarik, sosok tokoh pendiri Madzhab Ahlusunnah Wa al-Jama’ah ini, tak asing di telinga para sarjana Muslim, khususnya para mengkaji teologi Islam, dan kaum Muslimin secara umum, terlebih khusus para pengikut Ahlusunah Wa al-Jama’ah.
Abu Hasan al-Asya’ari merupakan salah satu tokoh penting dalam tongak perkembangan teologi di dunia Islam, pemikiran paradoksnya muncul pada awal-awal abad ketika mulai melemah perkembangan kelompok Mu’tazilah,sebagai ruju kan al-Asyari pengaruhnya mulai memudar di mata masyarakat kala itu, bahkan waktu itu dalam kepercayaan penguasa pun sudah tidak begitu dianggap penting.
Selanjutnya Al-Asy’ari banyak bersebrangan dengan kelompok Muktazilah. Sebelumnya Mu’tazilah sebagai referensi penting dalam sejarah hidup pemikiran Al-Asy’ari, sebelum mendirikan Ahlusunnah Wal Jama’an, Muktazilah merupakan sekte (firqah) yang membentuk pemikiran Al-Asy’ari.
Inti ajaran Al-Asy’ari, menurut sejumlah sumber adalah sikapnya yang moderat terhadap doktrin teologi lain. Asy’ari menggunakan akal untuk menyikapi masalah teologis, di satu sisi, namun ia juga percaya penuh kepada teks al-Qur’an dan al-Hadits sebagai argumentasi suci yang tidak boleh dihindari, di pihak lain. Sikap moderat inilah yang dikemudian hari melambungkan seoarang al-Asyr’ari sekaligus membedakan dirinya dengan kelompok Muktazilah, Al-Asy’ari menjadi banyak pengikut di kalangan kaum muslimin dari pada Madzhab-Mazhab teologi Islam lain.
Nama panjang Al-Asy’ari adalah Abu Hasan bin Isma’il al-‘Asy’ari al-Bashri (260-323 H) lahir di Bashrah dan wafat di Baghdad. Al-Asy’ari semula merupakan pemuka Mu’tazilah (rabi al-Mu’tazilah) sekaligus menjadi murid kesayangan seorang teolog dan filsuf Mu’tazilah, Imam al-Jubai (849-946 M), Al-Jubai merupakan seoarang ulama Mu’tazilah yang sangat dikagumi, dan sigani di kalangan kelompok Muktazilah, ia memiliki ilmu yang cukup luar biasa.Abu Hasan Al-Asy’ari banyak dibimbing oleh al-Jubai tentang pemahaman Mu’tazilah dan Al- Asy’ary banyak mengambil pendapat-pendapat Mu’tazilah sebagai rujukan pikiran teologisnya.
Abu Hasan Al-Asy’ari sebagaimana dijelaskan oleh Tajudin Subki (727-771 H), menurut catatan al-Subki selama 40 tahun al-Asy’ari bermakmum pada pemikiran Mu’zilah. Lalu di dikemudian hari, al-Asy’ari melepaskan faham Mu’tazilah. Al-Asy’ari memiliki pandangan sendiri, selajutnya Al-Asy’ari menjadi tonggak penting dalam sejarah berdirinya Alhulusunnah wal Jama’ah setelah lepas dari kelompok Mu’tazilah.
Akan tetapi sejumlah kalangan pemikir kontemporer banyak mempertanyakan dan mungkin menyayangkan, bahkan tak sedikit yang mengkritisi keputusan al-Asy’ari tersebut, ada yang mengatakan bahwa dengan tanpa alasan yang jelas al-Asy’ari meninggalkan Mu’tazilah tersebut, katanya. Bagi pengkritiknya merasa tidak yakin Al-Asya’ari meningalkan pemikiran Mu’tazilah begitu saja, yang mana selama 40 tahun al-Asyari pernah belajar dari pemikiran Mu’tazilah.
Banyak para sarjana Timur maupun Barat mengkritisi soal keputusan al-Asyari yang melepaskankan diri dari faham Mu’atzilah tersebut. Kritik mereka bahwa alasan-alasan yang mengemuka secara umum adalah bersumber dari pengikut al-Asy’ari sendiri, yaitu seperti dari Tajudin Subki (727-771 H/1327-1370 M) dan Ibnu Asakir ( 499-563H/1105-1176 M), bahkan Khatib al-Baghdadi (392-463 H/ 1002-1071 M) juga menulis soal alasan tersebut dalam karyanya Tarikh al-Baghdad. Oleh sebab itu tak sedikit pihak yang membuat ragu atas keputusan al-Asya’ari meninggalkan sepenuhnya faham Mu’tazilah.
Dari sumber-sumber pengikut Al-Asy’ari, setidaknya ada dua sebab yang mengemuka, mengapa al-Asya’ri meninggalkan paham Mu’tazilah, alasan pertama al-Asy’ari keluar dari pemikiran Mu’tazilah, pada suatu malam Al-‘Asya’ari bermimpi; dalam mimpi tersebut ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tetang kebenaran Alhul Hadits dari pada kebenaran kelompok Mu’tazilah. Sebab kedua Al-Asy’ari meningalkan Mu’tazilah adalah ketidakpuasan Al-Asyari dalam perdebatan antara dirinya dan gurunya Imam al-Juba’i, dan dalam perdebatan tersebut al-Juba’i tidak mendapat jawaban memuaskan dari pertanyaan al-Asy’ari sebagai murid al-Juba’i.
Menurut sejumlah orang yang tidak puas atas keputusan al-Asya’ari, sering mengatakan bahwa alasan-alasan inilah yang sering diajukan oleh para pengikut al-Asy’ari mengapa Abu Hasan al-Asy’ari keluar dari faham Mu’tazilah.
Oleh karena itu dalam catatan Harun Nasution (w.1998) mengatakan ada sejumalah sarjana Muslim seperti Ahmad Mahmud Subhi, Ahmad Amin, dan Ali Musthafa Ghurabi, ketiga pemikir tersebut agak kritis dalam persoalan keluarnya Al-Asy’ari dari Muktazilah, bahkan ada yang mengatakan harus hati-hati menerima argumrntasi atas keluarnya Al-Asy’ari disebabkan alasan-alasan yang dijelaskan tadi.
Lebih jauh Ali Musthafa al-Ghurabi mengatakan, tak mungkin seoarang Al-Asy’ari yang sudah lama bersama Muktazilah selama 40 tahun menganut pemahaman Mu’tazilah, lalu mumbuat kita tidak mudah percaya bahwa Al-Asy’ari meninggalkan paham Mu’tazilah hanya kerena perdebatan dengan Al-Juba’i yang tidak dapat memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan pada Al-Asy’ari.
Terlepas dari alasan-alasan tersebut menjadi perdebatan di atas atau ketidak singkronisasi fakta historis yang sepihak, yaitu hanya bersumber dari kalangan pengikut al-Asya’ari saja, yang banyak menjelaskan alasan keluarnya al-Asy’ari dari paham Mu’tazilah tersebut.
Namun, di sini kita bisa melihat dalam aspek lain yaitu ada keadaan skeptis dari seoarang al-Asy’ari terhadap ajaran Mu’tazilah yang diikutinya tersebut. Tesis ini berawal dari asumsi apa yang dijelaskan banyak para sejarawan Islam dan para sarjana teologi Islam yang memperkuat penjelasan tersebut, bahwa Al-Asy’ari pernah mengasingkan diri di rumah (I’tizal) cukup lama berdiam diri di rumah tidak tidak melakukan aktifitas di luar, selama 15 hari berdiam dirumah untuk merenungkan doktrin-doktrin Mu’tazilah. Setelah selesai dalam refleksinya, selajutnya al-Asy’ari keluar rumah, tepat pada hari Jum’at ia mendatangi manusia yang berada di dalam masjid dan naik ke atas mimbar lalu berkata:
“معاشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت، فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجّح عندي شيء على شيء، فاستهديت لله فهداني إلى اعتقاد ما أودعته فيكتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده، كما انخلعت . من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه، ورمى به“
“Para hadirin sekalian, selama ini saya mengasingkan diri, yang mana tak lain untuk merenungkan tentang penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil yang diberikan masing-masing kelompok. Dan saya kira argumentasi masing-masing tersebut pada dasarnya tidak saling melemahkan antara satu sama lain di atas yang lainnya. Oleh karenya saya memohon petunjuk dari Allah dan atas petunjuk-Nya, dan sekarang saya melepaskan diri dari semua keyakinan yang lama dan menganut pada keyakinan yang baru yang saya tulis dalam kitab-kitab ini. Keyakinan lama saya buang sebagaimana aku melepakan baju ini lalu aku melempar baju tersebut”.
Sikap sekeptis dalam diri al-Asy’ari terhadap doktrin Mu’tazilah yang kemudian mendoronya untuk melepaskan dari ajaran Mu’tazilah. Sikap al-Asy’ari tersebut menimbulkan banyak perdebetan para sarjana Muslim dikemudian hari. Berbagai interpretasi muncul dari berbagai pihak tetang soal ini, sejumlah sumber mengatakan bahwa keluarnya al-Asy’ari dari doktrin Mu’tazilah, karena al-Asya’ari secara fiqh penganut Madzhab Syafii (150-205 H) yang mana Syafi’i sangat berbeda pandangan dengan doktrin Mu’tazilah, khususnya soal pendapat tentang al-Quran, Imam Syafi’i berpendapat bahwa al-Quran bukan ciptaan (Gair al-Makhluk), tetapi bersifat qadim dan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti, sedangakan doktrin Mu’tazialh adalah kebalikannya. Sedangkan menurut sumber lain yang umum mengatakan adalah ketidak puasan al-Asy’ari pada al-Juba’i atas tidak memperoleh jawaban yang puas dari al-Jubai atas arguntasi-argumntasi dalam salah satu perdebatan mereka berdua.
Argumentasi atau tasfir mengenai al-Asy’ari menanggalkan ajaran Mu’tazilah tersebut banyak para sarjana modern menolak atas tidak memuaskan kelompok-kelompok ini, alasannya adalah keluarnya al-Asya’ari dari Mu’tazilah menurut mereka tidak masuk akal hanya oleh alasan-lasan sepele tersebut, al-Asy’ari bisa melucuti semua ajaran yang pernah dipelajarinya selama 40 tahun, hanya dengan 15 hari merenung bisa begitu saja menukar Madzhab. Namun bagi para pengikut al-Asy’ari bahwa keluarnya pemuka Ahlu Sunnah tersebut dari ajaran Mu’tazilah sudah cukup masuk akal dan sangat bisa dimengerti bahkan penlusurannya sudah merujuk pada data-data sejarah yang sangat memadai.
Saya kira perlu ada semacam penelusuran lebih lanjut dalam soal perdebatan al-Asy’ari yang melucuti ajaran Mu’tazilah tersebut, jika benar kalau dulunya seoarang penganut faham Mu’tazilah. Mungkin bisa saja melakukan kebenaran tersebut dicari akarnya lewat pendekatan lain tidak hanya data-data historiografi sepihak, atau juga mengajukan data-data pihak lain, satu argumnentasi berbeda tetang sejarah tentang keluarnya al-Asy’ari dari Mu’tazilah dari lewat data-data yang sangat memadai atau bahkan mungkin melalui pendekatan antroplogis, filologi, etnologi, arkeologis dan alat bantu ilmu sejarah lain. Juga penting dalam menelaah soal pedebatan itu, dengan memotret jalan lain seperti pendekatan soal konflik sosial-politik di masa itu, bahkan kita harus mampu mepertpertimbangkan secara khusus dalam asumsi-asumsi lain di luar pendekatan di atas tadi, dan ini bisa benar, bisa saja tak sepenuhnya salah.****
Penulis. Ws Aziz (Jurnalis, Koordinator Program di Forum Jurnalis Jawa Barat).
Sumber Bacaan :
1). Ibnu Khaldun. Muqadimah, hal. 490. Jilid 1. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Libanon. 2006.
2). Dr. Abdul Hadi al-Fadli. Khulasah Ilm al-Kalam, hal.11. Dar al-Ta’aruf al-Matbu’ah. Suriah. 1988.
3). Ahmad Amin. Dzuhr al-Islam, hal.767. juz 3. Hindawi. Kairo. 2013.
4). Harun Nasution. Teologi Islam, hal. 66. UI-Press. Jakarta. 2010.
5). Muhammad Abu Zahrah. Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah, hal.167. Darul Fikr al-Arabi. Kairo. 2009.
6). Ahmad Amin. Dhuhr al-Islam, hal. 769. Juz. 3. Hindawi. Kairo. 2013.